Aswajabuleleng | (Dilansir Dari Bahtsul Masa’il Maudhu’iyah Fiqhul Udhiyah LBM PCNU Sidoarjo Ahad 26 Juni 2022).
Pada dasarnya hukum berqurban adalah Sunnah Mu’akad dalam ranah personal atau Sunnah ‘ainiyah, dan berlaku Sunnah kifayah dalam tatanan kolektifitas satu keluarga jika salah satu dari anggota keluarga tersebut sudah ada yang menunaikannya maka gugur tuntutan kesunnahan bagi yang lain. Namun tidak menutup adanya pahala Sunnah bagi yang melakukan dari anggota keluarga tersebut setelah ada yang melakukannya terlebih dahulu.
Hukum berqurban juga bisa menjadi wajib karena faktor eksternal, yaitu ketika disertakan dalam suatu ucapan nadzar baik nadzar murni sebagaimana seseorang bernadzar untuk berqurban di tahun tertentu “Demi Allah saya akan berqurban di tahun 2022”, atau nadzar untuk mewujudkan suatu yang diinginkan sebagaimana bernadzar akan berqurban jika bisa mendapatkan beasiswa doctoral “Demi Allah jika saya mendapatkan beasiswa doctoral, saya akan berqurban di tahun 2022”.
Dalam ranah nadzar, tidak ada problematika dilematis dikalangan masyarakat baik para pakar fiqih atau masyarakat awam sendiri, karena perbincangan tentang kewajiban qurban sebab nadzar mudah untuk dijelaskan dan difahami oleh berbagai kasta masyarakat. Hanya saja, dalam kajian fiqih qurban, ternyata terdapat diskursus konsekuensi qurban menjadi wajib tidak hanya sebab nadzar sebagaimana yang telah disebutkan.
Hukum qurban juga bisa menjadi wajib sebab Ta’yin, atau menentukan hewan mana yang diqurbankan seperti menunjuk kambing yang dimiliki dengan mengucapkan “Kambing ini adalah qurbanku”, atau seperti menjadikannya sebagai hewan qurbn dengan mengucapkan “aku jadikan kambing ini sebagai qurbanku”.
Problematika ini yang sangat debatable baik teoritis maupun praksis, karena dari kajian para ulama, banyak yang mencantumkan permasalahan yang relate menimbulkan dilematika tersebut, seperti konsekuensi wajib qurban sebab ta’yin yang muncul dari ucapan orang awam ketika mereka membeli hewan untuk diqurbankan sejak permulaan tahun jauh sebelum masuk bulan Dzulhijjah ketika mereka ditanya untuk apa membeli hewan tersebut mereka menjawab “ini untuk qurban” meskipun mereka tidak mengetahui rentetan konsekuensi hukum wajib dari sekedar ucapan yang mereka jawabkan meskipun telah dikarifikasi bahwa ucapan mereka tersebut hanya sebatas memberi kabar atau sekedar memberi tahu bahwa dia akan melakukan ibadah qurban sunnah, dan tidak bertujuan untuk melaksanakan qurban wajib.
Hal ini menjadi dilematis bagi masyarakat awam jika dipandang dari sisi konsekuensi qurban wajib. Bagaimana tidak, sedangkan bagi Mudhahhi (yang berqurban) tidak diperbolehkan sama sekali untuk memakan daging hewan qurbannya, bahkan wajib untuk mensedekahkan keseluruhan dari daging hewan tersebut.
Tidak dipungkiri, bahwa hukum seperti ini secara realita juga sangat jarang difahami oleh masyarakat awam pada umumnya, karena budaya dialog bertanya dan memberi kabar adalah suatu hal yang lumrah terjadi, sedangkan dialog “Ini adalah hewan qurbanku” atau sejenisnya adalah mengandung konsekuensi hukum yang tidak terduga.
Penulis sempat berfikir, apakah dialog seperti ini adalah salah satu budaya yang hanya ada di masyarakat arab yang memang dengan hanya mengatakan dialog ta’yin qurban seperti diatas sudah mewakili terhadap wujudnya nadzar atau adanya keterikatan suatu ibadah yang wajib untuk dilakukan. Sebagaimana dialog dalam diskursus Dzihar yang ternyata merupakan budaya talak masyarakat jahiliyah yang menurut masyarakat kita sendiri dengan dialog itu bukan berarti menyamakan istri dengan wanita yang haram dinikahi atas dasar talak, akan tetapi atas dasar pujian dan sanjungan pada umumnya.
Dilematika hukum ini juga akan memunculkan disorientasi pemahaman masyarakat awam tentang qurban wajib dalam ranah praksis yang menuntut harus selalu memberikan tambahan penjelasan sebagaimana dialog “Ini qurban sunnahku”, ketikan menyerahkan hewan qurban kepada panitia atau ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan tentang status hewan yang dibeli atau yang dipunyai. Atau menjawab dengan mengatakan “Hewan ini akan kami sembelih, dan kami makan pada hari raya ied al-Adha” untuk tidak terjerat vonis qurban wajib.
Diskursus ini tidak menutup adanya perkhilafan yang terjadi dikalangan para ulama, sebagaimana perdebatan yang penulis temukan dibeberapa kitab yang mencantumkan pembahasan ini seperti di alenia kelima diatas, dan menjadi pendapat mayoritas ulama mutaqaddimin. Berbeda dengan ulama muta’akhirin yang lebih memberikan beberapa catatan dan tidak langsung memfonis mutlak, dari kalangan mereka tentang bahasan ini yang paling disebut adalah al-Sayyid Umar al-Bashri.
Sayyid Umar al-Bashri lebih merinci kejadian tersebut, beliau tidak langsung memvonis hewan itu menjadi qurban wajib karena memandang tujuan dan maksud si pemilik hewan antara dia emang benar-benar men-ta’yin atau menentukan atau menyatakan dengan tegas bahwa hewan tersebut sebagai hewan qurbannya atau hanya sekedar memberikan kabar (ikhbar) bahwa dia menunjukkan hewan tersebut nanti yang akan dia gunakan untuk beribadah qurban, jika yang dimaksud adalah opsi kedua maka jelas menurut beliau hewan tersebut tidak menjadi qurban wajib.
Begitu pula al-Adzri’I, menurut beliau kasus diatas sekilas tampak seperti sekedar ungkapan yang berujung hukum wajib qurban, namun jika diteliti dialog tersebut lebih menyerupai bentuk iqrar atau pengakuan dan penetapan sehingga tidak janggal jika sampai menimbulkan hukum qurban wajib. Lebih lanjut Adzri’I dalam kitab al-Qala’id, memaparkan bahwa jika yang dikehendaki dari ungkapan “ini adalah qurbanku” adalah qurban Sunnah sebagaimana urf atau adat yang telah berlaku dimasyarakat sekitar, maka jelas tidak menjadi qurban wajib. Pendapat Adzri’I ini bayak disetujui oleh ulama muta’akhirin yang lain sebagaimana Sayyid Abdullah bin Husain Balfaqih .
Lebih jelas lagi, Muhammad bin Ahmad al-Syathiri dalam Syarh al-Yaqut al-Nafis menegaskan sebagian muta’akhirin tidak mengkategorikan sebagai ta’yin qurban wajib menitikberatkan orang awam mengalami hal yang dilematis, mereka tidak mengetahui makna dan konsekuensi dari apa yang mereka ucapkan dan juga sama sekali tidak berniat untuk bernadzar, memanadang ekspresi dar dialog tersebut adalah hanya sekedar menyusun kata untuk memberi tahu, bukan untuk meng-iqrar-kan hewan itu sebagai qurban wajib, maka perlu adanya pembeda antara niat nadzar dengan niat hanya sekedar ikhbar.
Overall, diskursus ini adalah hal yang disepakati oleh kedua pentarjih madzhab syafi’i, yakni al-Haitami dan al-Ramli. Oleh karena itu mutaqaddimin dan kebanyakan ulama tetap mengkategorikan sebagai qurban wajib tanpa melihat kontekstualitas dialog dari masyarakat awam dan masyarakat global yang mempunyai budaya Bahasa dan dialog yang menyebabkan berbeda-bedanya interpretasi. Akan tetapi tidak ada boikot tertentu untuk mengikuti pendapat sebagian muta’akhirin yang lebih bisa memadang kontekstualitas dan budaya masyarakat awam yang memang pendapat yang kedua inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Wallahu A’lam bi al-Shawwab.
KH. Ma'ruf khozin memberikan penegasan dengan menitik beratkan dengan mengatakan "Nderek Qaul Marjuh mawon sebab Li Umum Al-Balwa (ikut qoul yang diunggulkan saja sebab memandang keumumannya yang berdampak kurang kondusif dimasyarakat). Boten sedoyo masyarakat saget mondok (tidak semua masyarakat itu dapat belajar dipondok), menawi langsung diparingi semerap akan terkejut padahal sampun gadah semangat berkurban (kalau langsung dikasih tahu akan terkejut padahal sudah mempunyai semangat tinggi untuk berkurban).
Editor : Aly Mas'ud


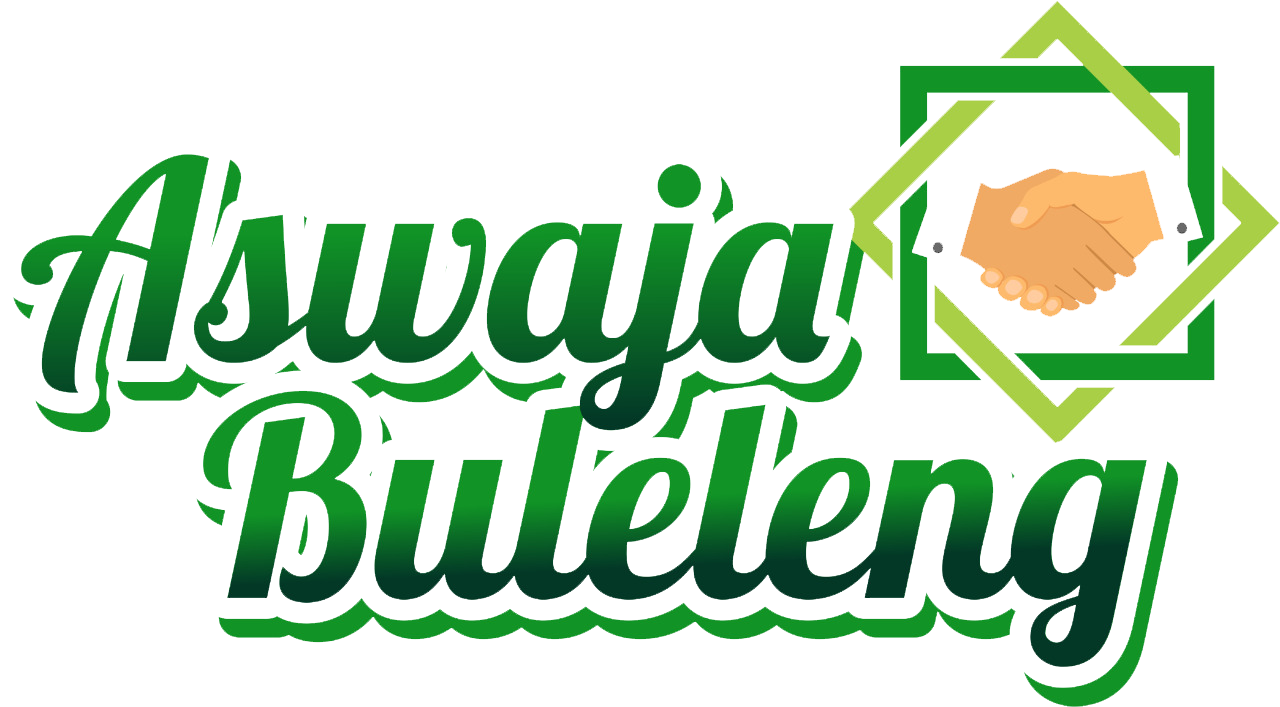







0 Comments